Bahasa jurnalistik kerap dipandang secara sinis. Tidak sedikit yang menuduhnya sebagai perusak bahasa. Bahasa media massa dianggap longgar terhadap kaidah, terlalu sederhana, bahkan cenderung menurunkan standar kebahasaan. Padahal, bahasa yang digunakan para pewarta tetaplah bahasa Indonesia. Ia bukan bahasa lain, melainkan ragam penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi massa.
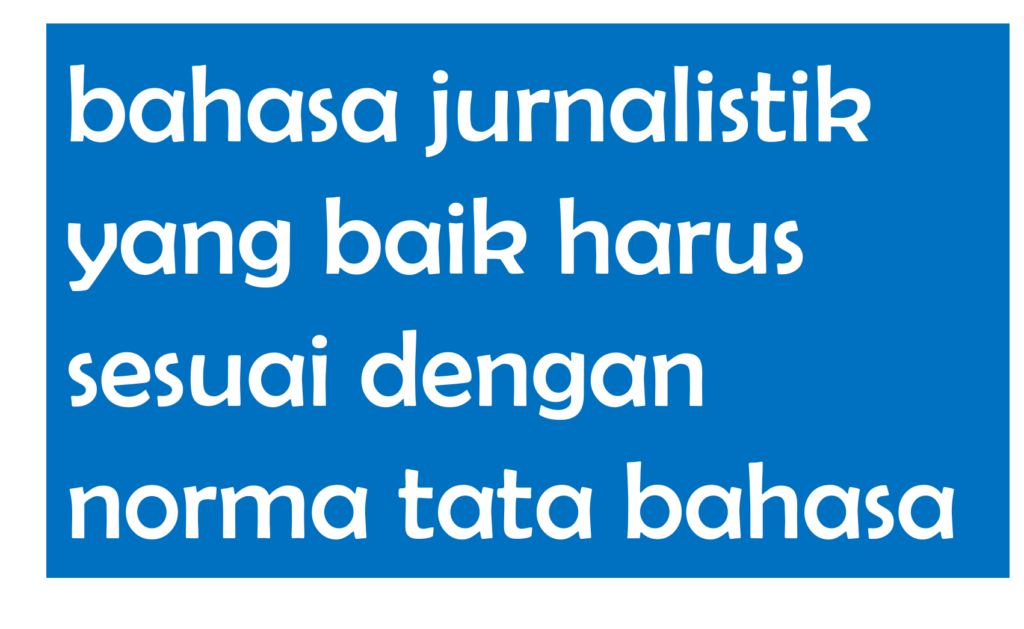
Sejumlah pakar bahasa telah menegaskan hal tersebut sebagaimana dikutip Sarwoko (2007) dalam buku Inilah Bahasa Indonesia Jurnalistik. Wojowasito (via Anwar, 1984:1) menyatakan bahwa bahasa jurnalistik yang baik harus sesuai dengan norma tata bahasa, mencakup susunan kalimat yang benar dan pilihan kata yang tepat. Anton M. Moeliono (1994) menempatkan laras bahasa jurnalistik dalam kategori ragam bahasa baku. Dengan demikian, secara normatif, bahasa jurnalistik tidak berada di luar sistem bahasa Indonesia.
Bahasa jurnalistik masuk era ketergesaan
Yang membedakan bahasa jurnalistik yang acap juga disebut bahasa pers dari ragam lain bukanlah kaidah dasarnya, melainkan fungsi komunikatifnya. Bahasa jurnalistik hadir untuk menyampaikan informasi secara cepat, jelas, dan efektif kepada khalayak luas. Rosihan Anwar (1984:1) menyebut sifatnya yang khas: singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Moeliono (1994) menambahkan adanya ekonomi kata dan kecenderungan pemendekan kalimat. Jus Badudu (1992:62) menegaskan prinsip kesederhanaan, keteraturan, dan efektivitas.
Perbedaan persepsi sering muncul karena bahasa media massa dibandingkan dengan bahasa buku ilmiah atau karya akademik. Bahasa buku memang menuntut kelengkapan argumentasi dan struktur yang lebih formal.
Bahasa media massa, sebaliknya, mengutamakan keterbacaan dan kecepatan pemahaman. Dalam perspektif linguistik fungsional, perbedaan ini merupakan persoalan register dan konteks situasi, bukan persoalan benar atau salah. Register bahasa, menurut Halliday (1978), selalu ditentukan oleh medan wacana (field), pelibat (tenor) , dan sarana komunikasi (mode) yang digunakan.
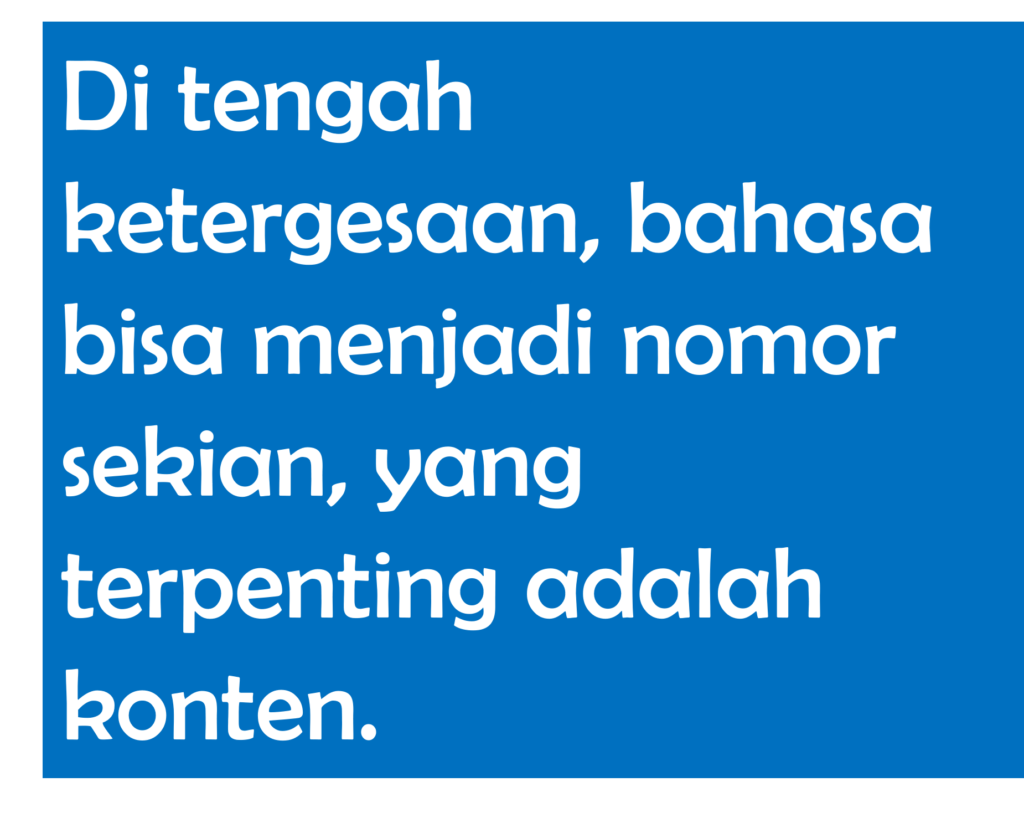
Perubahan terbesar justru terjadi ketika konteks situasi itu sendiri mengalami transformasi. Jika pada era media cetak redaksi masih memiliki ruang waktu yang relatif longgar untuk menyunting dan mematangkan naskah sebelum terbit, maka dalam lanskap digital ritme tersebut berubah drastis.
Media kini beroperasi dalam siklus produksi yang nyaris tanpa jeda. Kecepatan menjadi tuntutan struktural. Dengan kata lain, kita tidak hanya berada dalam perbedaan register, tetapi juga dalam perubahan ekosistem komunikasi—sebuah era ketergesaan yang membentuk ulang praktik jurnalistik.
Praktik jurnalistik semacam ini yang juga menjadi kegelisahan para pemerhati bahasa jurnalistik. Kegelisahan yang masuk akal. Di tengah ketergesaan, bahasa bisa menjadi nomor sekian, yang terpenting adalah konten. Bahasa media bisa makin rusak? Entahlah, belum ada penelitian mengenai hal ini.
Baca juga:
Judul sebagai Berita Terpendek
Kata Penat dalam Jurnalistik Digital: Frasa yang Bikin Bertele-tele
Bahasa Jurnalistik dalam lanskap digital
Apakah di era digital, bahasa jurnalistik juga mengalami perubahan? Boczkowski (2004) menjelaskan bahwa dalam ruang redaksi digital, tekanan kompetisi dan kecepatan publikasi mempengaruhi proses produksi berita, termasuk verifikasi dan penyuntingan. Adapun Westlund, dkk. (2025) menyatakan bahwa perubahan media akan mempengaruhi praktik produksi dan distribusi berita, termasuk aspek bahasa yang digunakan dalam konten jurnalistik digital. Perubahan tersebut terutama terjadi pada cara berita diproduksi, dikemas, dan diedarkan melalui platform digital.
Memasuki era digital, karakter bahasa jurnalistik tidak berubah secara prinsipil, tetapi mengalami intensifikasi fungsi. Informasi kini dikonsumsi melalui layar gawai, sering kali dalam bentuk judul, notifikasi, atau cuplikan singkat. Khalayak tidak lagi membaca secara linear dan tuntas, melainkan selektif dan cepat. Dalam konteks ini, prinsip singkat, padat, dan jelas menjadi semakin krusial.
Namun, pada tataran prinsip linguistik, karakter dasar bahasa jurnalistik tidak berubah. Ia tetap berpegang pada kejelasan, kepadatan, dan efektivitas. Yang mengalami transformasi adalah strategi penyajiannya.
Dalam lingkungan digital, informasi dikonsumsi melalui layar gawai, sering kali dalam bentuk judul, notifikasi, atau cuplikan singkat. Khalayak tidak lagi membaca secara linear dan tuntas, melainkan selektif dan cepat. Dalam konteks ini, prinsip singkat, padat, dan jelas mengalami intensifikasi fungsi.
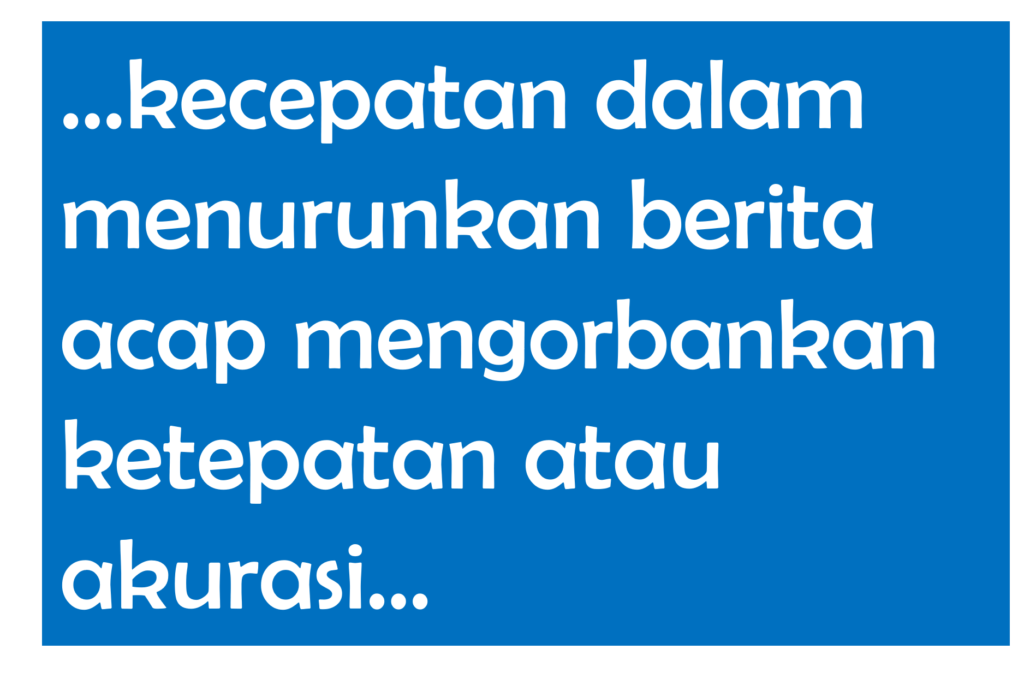
Namun, yang sering terjadi kecepatan dalam menurunkan berita acap mengorbankan ketepatan atau akurasi. Penyebabnya adalah breaking news. Karena adu cepat, media terkadang melakukan terkadang kesalahan data awal, misalnya di awal berita diturunkan ditulis “Diduga korban tewas mencapai 50 orang” tidak lama turun lagi berita yang menyatakan “korban tewas mencapai 12 orang”. Inilah yang dinamakan breaking news syndrome.
Kecepatan menurunkan berita dan dorongan untuk memperoleh klik banyak membuat media membuat judul provokatif (click-oriented headline). Judul seperti terkadang menyesatkan. Misalnya dibuat judul “Menteri X Akui Gagal Total!”, padahal yang dikatakan menteri adalah “Program ini belum mencapai target optimal”.
Tapi, di situlah tantangan era digital. Media harus seimbang antara kecepatan, keterbacaan, dan akurasi. Di sinilah bahasa jurnalistik tetap berpijak pada kaidah bahasa baku, sekaligus adaptif terhadap dinamika teknologi dan perilaku audiens.
Dengan demikian, bahasa jurnalistik dapat dipahami sebagai ragam bahasa Indonesia yang digunakan media massa untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada publik, dengan karakter khas yang bersifat fungsional, komunikatif, dan—dalam era digital—strategis.
• Tri Adi Sarwoko
Penulis adalah asesor penulis nonfiksi dan pengajar bahasa dan komunikasi
